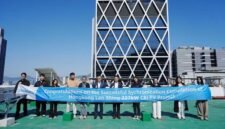BRPT melalui Barito Renewables menargetkan ekspansi energi hijau Indonesia hingga 2,4 GW pada 2032, menjadikannya pemimpin pasar domestik.
UBS memberi rating “Netral” karena pertumbuhan agresif BRPT disertai risiko realisasi proyek dan potensi sentralisasi kekuasaan energi.
Sektor petrokimia lewat Chandra Asri diprediksi pulih mulai 2026, ditopang proyek jumbo seperti Aster dan kolaborasi dengan Danantara.
ADA satu nama yang mendadak menjadi sinonim dengan transisi energi hijau Indonesia: Barito Pacific (BRPT).
Di balik nama korporasi itu, ada sosok taipan Prajogo Pangestu yang tak hanya membangun bisnis, tapi mulai menata ulang lanskap energi nasional.
UBS, bank investasi global, baru saja merilis riset yang memberi label “Netral” pada saham BRPT. Bukan karena kinerja buruk—justru sebaliknya.
Riset tersebut mencatat pertumbuhan agresif BRPT di sektor energi terbarukan.
Namun, di balik euforia kapasitas 965 MW hari ini dan target ekspansi hingga 2,4 GW pada 2032, muncul pertanyaan besar: apakah transisi energi kita sedang didominasi segelintir pemain?
Barito Renewables: Dari Panas Bumi ke Peta Global
Lewat anak usaha Barito Renewables (kode saham: BREN), BRPT bukan lagi sekadar pemain—mereka adalah pemimpin pasar energi terbarukan nasional.
Dengan kapasitas sekitar 965 megawatt (MW) per 2024, Barito menargetkan lonjakan hingga 2.400 MW (2,4 GW) dalam kurun 2027–2032. Fokusnya adalah pada dua sumber utama: panas bumi dan energi angin.
UBS memperkirakan kapasitas BRPT akan menembus 2 GW pada 2030, dengan CAGR (compound annual growth rate) sebesar 11% untuk periode 2024–2030.
Beberapa proyek strategis seperti Hamiding (Maluku Utara) dan South Sekincau (Sumatera) bukan hanya menjadi tulang punggung energi hijau Indonesia, tetapi juga dinilai potensial untuk ekspor ke pasar internasional.
Namun, dalam konteks global di mana transisi energi menjadi agenda demokratis—melibatkan banyak pihak dan teknologi—muncul risiko lain: terpusatnya kontrol energi baru di tangan sedikit pemain.
Baca Juga:
CGTN:Langkah Tiongkok Memperkuat Industri Unggulan Pedesaan guna Mendorong Revitalisasi Pedesaan
Coda Luncurkan Kampanye Regional untuk Cegah Penipuan Daring bagi Pemain Gim
Petrokimia: Bisnis Lama yang Tak Ditinggalkan
Meski narasi utama hari ini adalah energi hijau, BRPT masih mengandalkan kekuatan lama: petrokimia.
Melalui Chandra Asri Petrochemical (TPIA), BRPT masih menjadi raksasa dengan kapasitas produksi 4,2 juta ton per tahun—terbesar di Indonesia. Namun, profitabilitas sektor ini sempat tertekan akibat banjir pasokan dari Tiongkok.
UBS menilai kondisi tersebut akan segera pulih, ditopang oleh melambatnya ekspansi di Tiongkok, kebangkitan permintaan global, dan tensi geopolitik yang mengganggu rantai pasok dunia.
Proyeksi UBS: volume penjualan tumbuh 4% per tahun hingga 2027, dan laba bersih kembali mencetak angka positif mulai 2026.
Proyek Raksasa: Dari Aster hingga Chlor-Alkali
Di balik pemulihan sektor petrokimia, terdapat sejumlah proyek jumbo yang digadang-gadang menjadi katalis pertumbuhan.
Pertama, Proyek Aster—sebuah kawasan industri terintegrasi dengan kapasitas petrokimia 4,4 juta ton dan minyak 8 juta ton per tahun. UBS menilai nilai proyek ini mencapai US$4,3 miliar.
Baca Juga:
Kedua, proyek chlor-alkali senilai US$800 juta yang akan digarap bersama Danantara pada 2026.
Jika proyek-proyek ini terealisasi tepat waktu dan sesuai target, bukan hanya menambah nilai strategis BRPT, tapi juga menandai kebangkitan industri dasar nasional yang sempat tergencet.
Kalkulasi Investor: Di Mana Letak Nilainya?
UBS menilai BRPT menggunakan metode sum-of-the-parts (SOTP), di mana:
2. 69% nilai perusahaan berasal dari sektor energi terbarukan (dinilai menggunakan EV/EBITDA 12x),
2. Sektor petrokimia dinilai dengan discounted cash flow (DCF) dan WACC 7,3%,
3. Proyek Aster dipatok US$4,3 miliar,
4. Pembangkit listrik batu bara Indo Raya Tenaga juga masuk dalam model dengan WACC 10,7%.
UBS memperkirakan EBITDA BRPT akan tumbuh 19% per tahun dan laba bersih 45% per tahun dalam rentang 2024–2027.
Namun, rating “Netral” mencerminkan kehati-hatian pasar: ada potensi, tapi juga risiko, terutama pada waktu dan eksekusi proyek-proyek besar.
Sisi Lain yang Jarang Dibahas: Sentralisasi Energi?
Pertanyaan pentingnya bukan hanya soal berapa besar kapasitas yang bisa dibangun. Tapi juga: siapa yang membangunnya dan siapa yang mengendalikannya?
Dengan kian sentralnya peran BRPT dalam transisi energi, muncul kekhawatiran bahwa alih-alih demokratis, energi hijau justru akan mengalami “oligopolisasi baru”.
Saat ini, sejumlah negara mendorong pendekatan desentralisasi energi dengan teknologi terdistribusi (rooftop solar, mikrogrid, komunitas energi). Tapi di Indonesia, arah itu justru belum terlihat.
Jika energi hijau hanya dikendalikan korporasi besar, risiko baru mengintai: ketimpangan akses energi dan ketergantungan pada satu-dua entitas.
Mimpi Hijau, Realitas Abu-Abu
Prajogo Pangestu tak sekadar menjadi taipan energi, tapi juga simbol ambisi industri Indonesia untuk naik kelas di era transisi energi.
Namun, sebagaimana semua mimpi besar, akan selalu ada pertarungan narasi: antara pertumbuhan dan keadilan, antara dominasi dan demokrasi, antara keberlanjutan dan akumulasi.
Investor, analis, dan publik sepatutnya melihat BRPT bukan hanya sebagai kode saham, tetapi sebagai cerminan arah industri nasional.
Apakah kita sedang membangun sistem energi masa depan? Atau hanya mengganti mesin lama dengan cat yang lebih hijau?
Investor Jangka Panjang Disarankan Tetap Waspada
BRPT patut diapresiasi atas kontribusinya dalam mendorong transisi energi nasional.
Namun, regulator perlu memastikan agar pertumbuhan sektor energi hijau tidak menjadi ladang monopoli baru.
Akses energi yang adil dan terjangkau harus tetap menjadi prinsip utama pembangunan energi nasional.
Investor jangka panjang disarankan tetap waspada terhadap waktu realisasi proyek dan dampak eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan perubahan regulasi.***